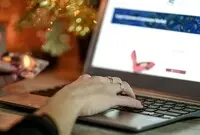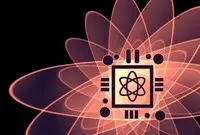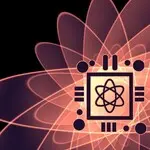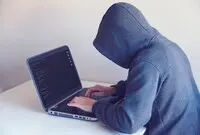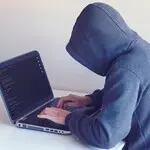Premanisme Digital: Sinergi Kekerasan dan Teknologi Siber
- Yudianto Singgih
- •
- 15 Mei 2025 20.25 WIB

Ilustrasi Cyber Security
Ringkasan
Di era digital saat ini, kekuasaan tidak lagi hanya dimanifestasikan melalui kekuatan fisik atau kehadiran di jalanan. Ia juga hadir secara senyap melalui layar, pesan anonim, dan algoritma. Ketika premanisme sebagai praktik kekuasaan informal terus berevolusi, muncul pertanyaan penting: apakah dunia maya kini juga menjadi arena baru bagi preman digital? Fenomena pemerasan daring, perundungan siber, dan penyebaran hoaks menunjukkan bahwa taktik lama mendapatkan ruang hidup baru—lebih tersembunyi, namun sama berbahayanya. Ringkasan ini merangkum fenomena mengenai bagaimana pola kekuasaan dan intimidasi yang sebelumnya terjadi di dunia fisik kini menunjukkan tanda-tanda konvergensi dengan modus kejahatan siber.
Premanisme dan kejahatan siber adalah dua fenomena yang tampaknya terpisah, namun memiliki banyak kesamaan dalam taktik, motivasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Premanisme di Indonesia, yang berakar pada praktik kekerasan, intimidasi, dan pemerasan dalam konteks sosial-politik, telah lama menjadi bagian dari dinamika sosial negara. Kelompok preman sering kali menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau politik melalui cara-cara ilegal.
Sementara itu, kejahatan siber merupakan ancaman yang semakin berkembang di Indonesia, terutama dengan maraknya serangan seperti phishing, ransomware, dan perundungan daring. Kejahatan siber tidak hanya mengancam individu, tetapi juga dapat merusak infrastruktur penting, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi berbagai sektor.
Analisis ini mengungkapkan adanya konvergensi antara premanisme dan kejahatan siber, terutama dalam aspek pemerasan dan rekayasa sosial. Premanisme tradisional, yang melibatkan intimidasi fisik, memiliki kesamaan taktik dengan serangan phishing atau scareware di dunia maya, yang sama-sama menggunakan ancaman untuk menekan korban agar membayar tebusan atau menyerahkan data pribadi. Selain itu, premanisme yang awalnya terbatas pada wilayah fisik kini mulai berkembang ke dunia digital, di mana kelompok preman dapat menggunakan teknologi untuk mengakses, menyebarkan informasi palsu, atau melakukan pemerasan siber.
Premanisme digital ini mencakup perundungan siber, kontrol atas wacana digital melalui penyebaran hoaks, serta penagihan utang ilegal online yang semakin marak di Indonesia. Keterlibatan kejahatan terorganisir dalam sektor-sektor ini menunjukkan bahwa premanisme fisik telah berevolusi ke ranah siber, menggunakan taktik yang serupa namun lebih tersembunyi dan sulit dilacak.
Sebagai respons terhadap perkembangan ini, diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kriminologi, sosiologi, dan keamanan siber untuk memahami secara holistik evolusi bentuk-bentuk kejahatan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat literasi digital, merancang kebijakan perlindungan siber yang lebih baik, serta meningkatkan penegakan hukum agar dapat mengatasi ancaman yang berkembang pesat ini.
Pendahuluan
Belakangan ini, isu premanisme kembali ramai diperbincangkan, terutama ketika praktik-praktik kekuasaan informal seperti pemalakan, intimidasi, dan kekerasan kembali mencuat ke ruang publik—baik dalam bentuk nyata maupun terselubung. Namun, di tengah derasnya transformasi digital, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah premanisme juga ikut bermigrasi ke dunia maya? Adakah bentuk baru dari praktik kekuasaan preman dalam ruang digital yang tampak tak berwujud namun tetap memaksa? Di saat kejahatan siber terus berkembang dan aktor-aktor digital semakin kompleks, menarik untuk menyelidiki apakah terdapat pola keterkaitan, bahkan konvergensi, antara premanisme tradisional dan kejahatan siber yang kini mengancam masyarakat Indonesia dari balik layar.
Premanisme merupakan fenomena sosial-politik yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini dicirikan oleh penggunaan kekerasan, intimidasi, dan pengaruh informal oleh individu atau kelompok untuk memperoleh penghasilan atau kekuasaan, sering kali melalui cara-cara di luar hukum. Premanisme tidak hanya mencerminkan bentuk kejahatan jalanan, tetapi juga menunjukkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat, dengan hubungan yang kompleks antara pelaku preman, aparat negara, aktor politik, dan struktur ekonomi informal (Ryter, 1998; Wilson, 2015).
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ranah baru kejahatan: ruang siber. Keamanan siber kini menjadi salah satu aspek strategis dalam perlindungan negara, organisasi, dan individu dari ancaman digital, termasuk kejahatan dunia maya seperti peretasan, pencurian data, penipuan daring, dan serangan ransomware (Suharto, 2021; Kaspersky, 2023). Indonesia termasuk negara dengan tingkat ancaman siber yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, terutama karena lemahnya literasi digital, rendahnya investasi pada infrastruktur keamanan siber, serta meningkatnya serangan terhadap sektor publik dan swasta (BSSN, 2023; Interpol, 2021).
Meskipun secara kasat mata premanisme dan kejahatan siber tampak berbeda—yang satu beroperasi di dunia fisik, dan yang lainnya di dunia maya—keduanya dapat menunjukkan keterkaitan dalam struktur, tujuan, dan modus operandi. Keduanya sering berakar pada motivasi ekonomi, memanfaatkan kelemahan sistem, dan mengejar kontrol atas ruang atau sumber daya, baik secara fisik maupun digital (Wall, 2007; Brenner, 2010).
Tulisan ini mengeksplorasi hubungan potensial antara premanisme dan kejahatan siber di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kriminologi, sosiologi, dan studi keamanan digital, kajian ini mencoba menjawab bagaimana bentuk kekuasaan informal seperti premanisme dapat bertransformasi atau berkolaborasi dalam ekosistem kejahatan digital yang sedang berkembang.
Mendekonstruksi Premanisme: Menelisik Lebih Dalam Dunia Kekerasan
Premanisme di Indonesia merupakan bentuk kekuasaan informal yang tumbuh di antara kekosongan atau kelemahan penegakan hukum, dengan karakteristik utama berupa kekerasan, intimidasi, dan praktik ekonomi ilegal. Istilah “preman” sendiri berasal dari kata Belanda vrijman, yang berarti "orang bebas", namun dalam konteks Indonesia, maknanya mengalami pergeseran menjadi sosok yang terlibat dalam kegiatan kriminal non-formal dan kontrol sosial melalui kekuatan otot (Ryter, 1998; Wilson, 2015).
Secara struktural, premanisme tidak selalu bersifat liar atau anarkis. Dalam banyak kasus, ia terorganisir dan memiliki hierarki kepemimpinan serta wilayah kekuasaan. Kelompok-kelompok preman sering kali mengelola “bisnis” berupa pungutan liar, pemerasan terhadap pelaku usaha lokal, penyediaan jasa keamanan ilegal, hingga menjadi alat politik bayangan melalui “sewaan” untuk aksi-aksi demonstrasi atau kampanye (Barker, 2006). Beberapa di antaranya bahkan memiliki hubungan historis dengan aparat keamanan dan partai politik, terutama sejak era Orde Baru ketika aktor non-negara digunakan untuk mengontrol masyarakat sipil (Aspinall, 2001; Hadiz, 2004).
Premanisme juga berkembang subur di tengah krisis sosial-ekonomi. Pengangguran, kesenjangan sosial, dan lemahnya akses terhadap peluang ekonomi formal menciptakan kondisi yang subur bagi munculnya kekuasaan informal seperti preman (Wilson, 2010). Dalam konteks ini, premanisme bukan hanya gejala kriminalitas, tetapi juga refleksi dari ketimpangan struktural dan absennya keadilan sosial.
Selain motif ekonomi, premanisme juga dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik. Kelompok-kelompok preman dalam beberapa kasus digunakan sebagai alat mobilisasi massa, penjaga wilayah kampanye, hingga penekan oposisi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan informal tidak selalu bertentangan dengan negara; ia bisa menjadi mitra taktis dalam distribusi kuasa (Robison & Hadiz, 2004).
Premanisme bekerja melalui ancaman kekerasan—baik simbolik maupun fisik. Taktik yang digunakan mencakup pemerasan, penciptaan rasa takut, hingga kontrol wilayah. Dalam banyak kasus, preman menjadi semacam "pemberi perlindungan" dengan memaksa aktor lokal membayar sejumlah uang agar “aman”—praktik ini mencerminkan bentuk racketeering yang sering ditemui dalam studi kejahatan terorganisir di berbagai negara (Gambetta, 1993).
Ruang Gelap Digital: Memahami Keamanan Siber dan Kejahatan Dunia Maya
Dalam era digital yang kian terhubung, keamanan siber telah menjadi isu sentral dalam lanskap keamanan nasional maupun global. Keamanan siber (cybersecurity) merujuk pada upaya melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan perangkat digital dari ancaman dan serangan yang bersifat merusak, mencuri, atau mengganggu (Von Solms & Van Niekerk, 2013). Serangan terhadap infrastruktur digital bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga bisa mengancam stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan kedaulatan negara.
Di Indonesia, kejahatan dunia maya menunjukkan peningkatan signifikan dalam dekade terakhir. Bentuk-bentuk serangan siber yang paling umum mencakup:
- Phishing, yaitu teknik manipulasi psikologis untuk mencuri informasi sensitif melalui tautan palsu atau email yang tampak sah (Kaspersky, 2023).
- Ransomware, yaitu perangkat lunak jahat yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya (Interpol, 2022).
- Peretasan (hacking), yaitu akses tidak sah ke dalam sistem komputer untuk tujuan pengintaian, pencurian, atau sabotase (Wall, 2007).
- Penipuan daring (online fraud), seperti investasi palsu, jual-beli fiktif, hingga skema ponzi berbasis platform digital (Furnell, 2019).
- Pencurian data pribadi, yang semakin sering terjadi seiring dengan lemahnya regulasi perlindungan data di Indonesia (BSSN, 2023).
- Perundungan siber (cyberbullying) dan pelecehan daring, yang menargetkan individu melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
- Spionase dan terorisme siber, yang melibatkan aktor negara atau non-negara dengan motif politik, ekonomi, atau ideologis (Brenner, 2010).
Motivasi di balik kejahatan siber sangat beragam. Dalam banyak kasus, keuntungan finansial menjadi pendorong utama, tetapi dalam beberapa konteks, motif politik, ideologis, dan bahkan balas dendam personal juga dapat menjadi pemicu (Andress & Winterfeld, 2013). Pelaku kejahatan dunia maya juga semakin beragam, mulai dari individu yang tidak memiliki keterampilan tinggi (script kiddies), hingga kelompok kriminal terorganisir, aktivis politik (hacktivists), dan bahkan aktor yang disponsori negara (nation-state actors) (Nurse, 2019).
Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar dalam keamanan siber:
- Rendahnya literasi digital masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan serangan berbasis rekayasa sosial (digital social engineering).
- Kurangnya investasi dan kesiapan infrastruktur keamanan digital, baik di sektor publik maupun swasta.
- Ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat, meskipun UU Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih terbatas (Setiadi, 2022).
- Tingginya frekuensi dan dampak serangan siber, laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah insiden siber tertinggi di Asia Tenggara (Interpol, 2022).
Kejahatan dunia maya kini bukan lagi sekadar ancaman teknis, melainkan sudah menjadi bagian dari lanskap kejahatan terorganisir. Ia melibatkan perencanaan matang, infrastruktur digital, hingga penggunaan taktik rekayasa sosial yang kompleks, ciri-ciri yang juga ditemukan dalam kejahatan dunia nyata seperti premanisme.
Lintasan Baru Kekuasaan Informal: Menautkan Premanisme dan Dunia Siber
Meskipun premanisme dan kejahatan siber tampak berada di domain yang berbeda—fisik versus digital—keduanya menunjukkan keterkaitan dalam berbagai aspek, mulai dari motif hingga modus operandi. Pemahaman atas hubungan ini penting untuk melihat bagaimana praktik kekuasaan informal di Indonesia dapat mengalami transformasi digital atau bahkan memperluas jangkauannya ke ruang siber.
Salah satu titik temu paling nyata antara premanisme dan kejahatan siber terletak pada taktik intimidasi dan pemaksaan. Dalam konteks premanisme, pelaku menggunakan ancaman kekerasan fisik, pemalakan, dan kontrol wilayah sebagai alat pemaksaan. Di dunia siber, taktik ini tercermin dalam bentuk rekayasa sosial (social engineering) seperti phishing, pretexting, atau scareware yang memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan korban untuk mendapatkan akses atau keuntungan (Mitnick & Simon, 2002).
Sebagai contoh, taktik scareware, yang menipu korban dengan pesan palsu tentang infeksi virus dan meminta pembayaran untuk "pemulihan", mirip dengan praktik preman jalanan yang menciptakan rasa tidak aman untuk kemudian menawarkan "perlindungan" dengan imbalan uang. Demikian pula, teknik pretexting atau penyamaran sebagai pihak berwenang dalam serangan siber juga merefleksikan perilaku preman yang menggunakan identitas palsu atau mengatasnamakan institusi tertentu untuk memanipulasi korban (Gragg, 2003).
Lebih jauh lagi, kelompok preman juga menunjukkan potensi untuk memanfaatkan alat digital dalam memperluas aktivitas kriminal mereka. Media sosial dan aplikasi pesan instan telah digunakan untuk menyebarkan intimidasi, fitnah, atau bahkan informasi palsu (hoaks) terhadap individu atau kelompok yang menjadi target mereka (Wilson, 2020). Preman digital ini menggunakan ruang daring sebagai "wilayah" baru, di mana kekuasaan mereka dijalankan bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekerasan simbolik dan psikologis melalui ancaman digital.
Kejahatan siber juga tidak bisa dipisahkan dari struktur kejahatan terorganisir. Laporan dari Interpol (2022) dan BSSN (2023) menunjukkan bahwa banyak serangan ransomware dan penipuan daring bersumber dari jaringan kejahatan lintas negara, yang memiliki sistem operasi canggih dan distribusi kerja yang menyerupai organisasi bisnis. Dalam konteks ini, premanisme sebagai bentuk kejahatan terorganisir di tingkat lokal memiliki peluang besar untuk terintegrasi atau berkolaborasi dengan jaringan siber kriminal global.
Contoh konkret dari titik konvergensi ini dapat ditemukan dalam laporan mengenai penagihan utang oleh pinjaman online ilegal di Indonesia, di mana pelaku digital (fintech ilegal) berkolaborasi dengan kelompok preman untuk melakukan penagihan fisik kepada korban (Komnas HAM, 2021). Ini menunjukkan bahwa garis antara ancaman digital dan kekerasan fisik semakin kabur, dan premis kekuasaan informal tradisional kini juga berlaku di dunia siber.
Kita juga bisa menyimpulkan bahwa kekuasaan informal di dunia fisik kini sedang mengalami transformasi bentuk, bukan hilangnya esensi. Di ranah digital, preman tidak selalu muncul dalam wujud klasik seperti kekerasan fisik atau pemalakan langsung, tetapi hadir melalui akun palsu, ancaman online, hingga kontrol algoritmik atas narasi dan opini publik.
Pemerasan Siber dan Ransomware: Titik Persimpangan Potensial
Salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang paling mencerminkan pola-pola premanisme tradisional adalah pemerasan siber, khususnya melalui serangan ransomware. Pemerasan, dalam konteks premanisme, biasanya melibatkan intimidasi atau ancaman kekerasan fisik terhadap korban yang menolak membayar “uang keamanan” atau bentuk pungutan liar lainnya. Di dunia digital, modus serupa dilakukan melalui penyanderaan data (data hijacking) dan ancaman akan menyebarkan, menghapus, atau mengenkripsi informasi penting jika tebusan tidak dibayarkan.
Indonesia mengalami peningkatan drastis serangan ransomware dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan terhadap institusi pemerintah dan infrastruktur penting, seperti insiden pada Pusat Data Nasional (PDN) yang sempat lumpuh akibat serangan siber pada 2023 (BSSN, 2023). Kelompok seperti LockBit, Brain Cipher, dan kelompok ransomware regional lainnya terindikasi sebagai pelaku yang aktif di wilayah ini (Kaspersky, 2023).
Walaupun tidak ditemukan bukti langsung yang menghubungkan kelompok preman tradisional dengan pelaku serangan ransomware tingkat tinggi, ada indikasi keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir lokal dalam memfasilitasi atau memanfaatkan hasil serangan tersebut. Studi oleh Wall (2010) dan Levi (2017) menunjukkan bahwa kelompok kriminal lokal sering kali menjadi “mitra distribusi” dalam operasi siber lintas negara, baik sebagai penyedia akses, sebagai pelaku rekayasa sosial, atau sebagai penyalur hasil pemerasan dalam bentuk uang tunai, identitas palsu, atau fasilitas lokal lainnya.
Lebih jauh, dalam konteks Indonesia, penggunaan istilah “preman” dalam dunia siber mulai muncul sebagai metafora baru untuk pelaku intimidasi daring atau pemerasan digital (Wilson, 2020). Bahkan, dalam forum daring dan repositori kode terbuka seperti GitHub, sempat ditemukan malware atau backdoor PHP dengan parameter bernama "preman", mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan siber lokal mungkin mulai mengadopsi identitas dan logika kekuasaan yang serupa dengan premanisme dunia nyata (Sutanto, 2023).
Pemerasan digital dan pemerasan fisik juga beririsan secara struktural dan psikologis. Keduanya bertumpu pada menciptakan rasa takut, tekanan waktu, dan ketidakberdayaan korban. Bedanya, di dunia digital, bentuk tekanan ini disampaikan melalui tampilan layar yang mengancam, sementara di dunia nyata, bisa melalui kunjungan fisik atau kekerasan verbal. Keduanya sama-sama menargetkan korban yang lemah secara sistemik dan memiliki kapasitas terbatas untuk membela diri secara hukum atau teknis (Brenner, 2010; Nurse, 2019).
Pemerasan siber melalui ransomware mencerminkan pergeseran logika kekuasaan premanisme ke ranah digital, di mana kontrol atas data menggantikan dominasi fisik atas ruang. Seperti preman yang menuntut “uang keamanan,” peretas menaklukkan sistem dan memaksa korban membayar tebusan. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi antara pelaku kekerasan fisik dan aktor siber mulai terlihat, menciptakan bentuk baru kejahatan terorganisir. Kemunculan istilah “preman” dalam ekosistem digital menunjukkan bahwa logika kekuasaan informal kini berevolusi di dunia maya, menuntut respons hukum dan sosial yang lebih adaptif.
Wilayah yang Berkembang: Premanisme di Alam Digital?
Di era transformasi digital, konsep kekuasaan dan dominasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Ruang siber—media sosial, platform komunikasi digital, hingga ekosistem ekonomi digital—telah menjadi arena baru di mana aktor non-negara seperti preman dapat memperluas pengaruh mereka. Ini menandai evolusi dari premanisme jalanan menuju bentuk baru yang dapat disebut sebagai premanisme digital.
Premanisme digital dapat didefinisikan sebagai praktik-praktik kekuasaan informal berbasis kekerasan simbolik dan psikologis yang dilakukan di ruang daring, dengan tujuan memperoleh pengaruh, kontrol, atau keuntungan ekonomi melalui taktik intimidasi, manipulasi, dan ancaman. Manifestasinya meliputi:
- Perundungan dan pelecehan siber terhadap individu atau kelompok tertentu melalui akun anonim atau massal. Dalam beberapa kasus, serangan dilakukan secara terorganisir dan berbayar (Wilson, 2020).
- Penguasaan wacana digital, dengan penggunaan bot, buzzer, atau akun palsu untuk menyerang lawan politik, menyebarkan hoaks, atau membentuk opini publik palsu.
- “Premanisme daring” melalui media abal-abal, di mana pelaku menyebarkan informasi bohong atau fitnah untuk menekan individu, pejabat, atau institusi demi keuntungan pribadi (Kominfo, 2022).
- Penagihan utang online dengan cara-cara intimidatif, termasuk mengakses kontak korban dan menyebarkan informasi pribadi secara ilegal (Komnas HAM, 2021).
Pergeseran ini menunjukkan bahwa logika kekuasaan preman yakni dominasi melalui rasa takut dan kontrol wilayah telah menemukan bentuk baru di dunia digital. Dalam hal ini, “wilayah” bukan lagi gang atau pasar tradisional, melainkan komunitas digital, grup media sosial, atau platform e-commerce.
Bukti semakin kuat ketika melihat keterlibatan kelompok kriminal terorganisir Indonesia dalam sektor-sektor seperti perjudian daring, pinjaman online ilegal, dan perdagangan data pribadi. Laporan dari Interpol (2022) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2023) mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu target dan sumber utama aktivitas digital ilegal di Asia Tenggara. Beberapa operasi ini bersifat lintas batas dan menunjukkan pola organisasi yang mirip dengan struktur premanisme klasik—hierarkis, kolektif, dan berbasis loyalitas serta kekerasan simbolik.
Lebih dari itu, legislator dan penegak hukum di Indonesia mulai menyadari pergeseran ini. Dalam berbagai forum kebijakan, telah muncul kekhawatiran mengenai "premanisme digital", yakni intimidasi dan pemaksaan melalui media sosial dan kanal daring yang dianggap memiliki daya rusak sama besar dengan kekerasan fisik.
Premanisme tidak menghilang di era digital, melainkan bertransformasi dalam bentuk dan mediumnya. Para pelaku tidak selalu menunjukkan kecanggihan teknis seperti peretas profesional, tetapi justru memperlihatkan kecanggihan sosial kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengeksploitasi relasi kuasa, ketakutan, serta kerentanan sosial yang ada di ruang digital. Dalam konteks ini, ruang siber telah menjadi locus baru kekuasaan informal, tempat di mana bentuk-bentuk dominasi dan pemaksaan lama mendapatkan medium baru untuk berkembang. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dipahami dan ditangani secara serius melalui pendekatan hukum, kebijakan keamanan nasional, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Kesimpulan
Premanisme dan kejahatan siber, meskipun pada awalnya tampak sebagai dua entitas yang berbeda—satu berakar pada dominasi fisik, satu lagi berbasis teknologi digital—menunjukkan pola keterkaitan yang semakin nyata dalam konteks sosial Indonesia yang dinamis. Analisis ini menunjukkan bahwa keduanya berbagi kesamaan fundamental: motivasi ekonomi, penggunaan taktik intimidasi, manipulasi psikologis, serta eksploitasi kelemahan sistem hukum dan sosial.
Konvergensi ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk:
- Pemerasan, baik secara fisik maupun digital, dengan logika paksaan yang identik: “bayar atau menderita”.
- Rekayasa sosial, yang digunakan oleh preman jalanan maupun pelaku siber untuk menipu, menakut-nakuti, atau menundukkan korban.
- Kontrol wilayah, yang kini juga terjadi di dunia siber melalui dominasi wacana, penguasaan jaringan, dan manipulasi algoritma.
- Kolaborasi antara pelaku kriminal fisik dan digital, yang terlihat dalam kasus pinjaman online ilegal, perjudian daring, dan kejahatan lintas batas lainnya.
Lebih jauh, fenomena ini menandakan evolusi bentuk kejahatan terorganisir di Indonesia. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, para aktor kekuasaan informal seperti preman tidak serta-merta tersingkir, melainkan beradaptasi dan bermigrasi ke ruang siber, mengadopsi strategi baru untuk mempertahankan pengaruh dan sumber penghasilan.
Untuk itu, pemahaman terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan interdisipliner:
- Kriminologi untuk memahami struktur sosial dan motif para pelaku.
- Sosiologi untuk mengurai konteks sosial-politik yang melanggengkan kekuasaan informal.
- Keamanan siber untuk merespons dan merancang kebijakan perlindungan di era digital.
Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil di Indonesia perlu menyusun respons yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap bentuk-bentuk kekuasaan baru ini. Literasi digital, reformasi hukum, penguatan kapasitas siber nasional, dan pemberdayaan komunitas lokal adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditunda.
Daftar Referensi
- Andress, J., & Winterfeld, S. (2013). Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners. Elsevier.
- Aspinall, E. (2001). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford University Press.
- Barker, J. (2006). Vigilantes and the State: Violence and Local Governance in Indonesia. Asian Politics & Policy, 8(3), 381–403.
- Brenner, S. W. (2010). Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace. Praeger.
- BSSN. (2023). Laporan Keamanan Siber Nasional 2022. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- Furnell, S. (2019). Cybercrime: The Reality of the Threat. Computer Fraud & Security, 2019(6), 5–9.
- Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Harvard University Press.
- Gragg, D. (2003). A Multi-Level Defense Against Social Engineering. SANS Institute Reading Room.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. Development and Change, 35(4), 697–718.
- Interpol. (2021). ASEAN Cyber Threat Assessment 2021. https://www.interpol.int
- Kaspersky. (2023). Cyber Threats in Southeast Asia: A 2023 Outlook. https://www.kaspersky.com/
- Kaspersky. (2023). Ransomware and the Rise of Extortion-as-a-Service in Southeast Asia. https://www.kaspersky.com/
- Kominfo. (2022). Paparan Fenomena Penyalahgunaan Media Daring untuk Pemerasan dan Penipuan. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Komnas HAM. (2021). Pelanggaran Hak dalam Pinjaman Online Ilegal.
- Levi, M. (2017). Organized Cybercrime and the Organization of Cybercrime. Economics of Crime, 9(2), 201–220.
- Mitnick, K. D., & Simon, W. L. (2002). The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security. Wiley.
- Nurse, J. R. C. (2019). Cybercrime and You: How Criminals Attack and the Human Factors That They Seek to Exploit. In Cybercrime and Psychology, 1–22.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon.
- Ryter, L. (1998). Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s New Order? Indonesia, 66, 45–73.
- Setiadi, A. (2022). Dinamika Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Hukum & Kebijakan Publik, 8(1), 65–78.
- Suharto, Y. (2021). Ancaman Siber dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 11(2), 134–155.
- Sutanto, E. (2023). Premanisme Digital: Studi Kasus Malware Lokal dan Identitas Kriminal Dunia Maya. Jurnal Keamanan Siber Indonesia, 1(2), 88–104.
- Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2013). From Information Security to Cyber Security. Computers & Security, 38, 97–102.
- Wall, D. S. (2007). Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Polity Press.
- Wall, D. S. (2010). Policing Cybercrimes: Situating the Public Police in Networks of Security within Cyberspace. Police Practice and Research, 12(2), 183–197.
- Wilson, I. D. (2010). The Rise and Fall of Political Gangsters in Post-Authoritarian Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 32(3), 401–419.
- Wilson, I. D. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics. Routledge.
- Wilson, I. D. (2020). Digital Gangsters: Premanisme dan Kekuasaan Informal di Era Media Sosial. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(2), 145–162.